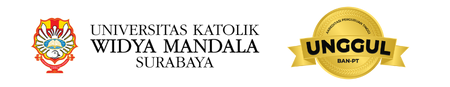[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kita kerap mendengar pernyataan “Indonesia adalah negara demokrasi”. Kenyataannya pun demikian. Setiap orang memiliki kebebasan dalam mengungkapkan pendapat, usulan dan kritik terhadap pemerintahan. Ciri selanjutnya adalah kesetaraan dalam merasakan kesejahteraan bersama. Demonstrasi, unjuk rasa, aksi massa, dan sebagainya adalah warna khas Indonesia sebagai negara demokrasi. Semua golongan ingin agar tuntutannya dipenuhi. Sayangnya, jalan kekerasan dan kerusuhan menjadi pilihan untuk menyalurkan aspirasi.
Semua orang mengenal bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan demi mencapai keadilan bersama. Selain itu, negara demokrasi memberikan kebebasan bagi setiap warganya untuk mengungkapkan aspirasi. Kesetaraan warga pun diakui di mata hukum. Tentu saja, kebebasan dan kesetaraan itu perlu memiliki kontrol, baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan kata lain, perlu ada rem yang tepat dalam mengatur negara demokrasi. Dalam hal ini, ideologi dan konstitusi negara perlu memerankan peran penting.
Inilah wajah demokrasi negara kita. Atas nama kebebasan, semua orang berbondong-bondong mengungkapkan pendapatnya. Implikasinya, golongan-golongan tertentu yang membawa nama mayoritas menuntut agar dipenuhi semua harapannya. Lihat saja, muncul ormas, front dan kelompok-kelompok tertentu yang ngotot untuk didengarkan suaranya. Mengganggu ketertiban sosial adalah hal lazim bagi aksi kelompok-kelompok tersebut. Belum lagi, internet menjadi ladang subur untuk mengungkapkan unek-unek, yang seringkali bernada hoax. Bila tidak hoax, paling tidak kelompok-kelompok tersebut mengungkapkan pendapat (liar) yang membawa nama demokrasi sebagai tiket menuju kebebasan.
Perlu diketahui, kenyataan di atas menunjukkan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang reaktif, bukan reflektif. Atas nama demokrasi, kebebasan disulap menjadi isu intoleransi yang picik. Atas nama demokrasi, kekerasan menjadi halal sebagai hegemoni (the driving force) demi mencapai kepentingan. Atas nama demokrasi, provokasi yang licik memiliki topeng yang menyuarakan kebencian. Atas nama demokrasi, pendapat dan kebebasan telah menyuapi banyak orang dengan makanan berita hoax. Pendek kata, demokrasi kita telah terjun bebas, sebebas-bebasnya.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5373″ img_size=”medium” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Atas nama kebebasan, sentimen warga diadukan bak ayam jago. Semua orang ingin diperhatikan. Bila tidak demikian, kekerasan akan berbicara. Tak heran, Presiden Joko Widodo dalam acara sebuah partai pada Rabu, 22 Februari 2017 lalu menilai bahwa demokrasi negara kita sudah kebablasan tanpa rem. Demokrasi kita yang selayaknya santun telah berevolusi menjadi obsesi liar (imagined democracy). Akibatnya, lahirlah artikulasi politik ekstrem, misalnya liberalisme, radikalisme, fundamentalisme bahkan terorisme.
Sebuah ekstrem dari Sokrates menyebutkan bahwa negara tidak dapat mencapai keadilan apabila menerapkan demokrasi. Menurutnya, tidak mungkin negara dapat berkembang apabila menyerahkan pemerintahan pada banyak kepala. Senada dengan itu, Plato muridnya juga menuduh demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang buruk setelah tirani. Ekstrem ini menyebutkan bahwa kebebasan dalam demokrasi pasti membawa sikap liar bagi semua orang. Tak heran, muara kedangkalan demokrasi adalah tirani yang nampak manis di awal tapi busuk di dalam.
Seorang filsuf kontemporer, John Rawls melihat demokrasi secara lebih optimis. Menurutnya, frase “terbuka secara sama” (equally open) memberikan prinsip kesempatan adil bagi semua orang. Pertama, interpretasi demokrasi harus terbuka secara adil bagi semua orang. Kedua, demokrasi perlu menjamin kesempatan yang sama bagi semua pihak dengan kombinasi prinsip diferen, yakni prinsip yang menjamin kesejahteraan masyarakat secara ideal. Perlu diingat, uraian tersebut juga mengandaikan bahwa semua orang wajib memperhatikan perbedaan-perbedaan objektif di antara semua warga (toleransi).[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Di masa sekarang, Franz-Magnis Suseno menyebut demokrasi tersebut sebagai democrazy. Kebebasan yang liar telah mencederai nilai demokrasi yang sejati. Relevansinya, barangkali semua pendapat kita melalui media internet maupun obrolan-obrolan ringan juga merupakan demokrasi yang reaktif, yakni tanggapan liar yang mengedepankan perasaan ketimbang akal sehat. Jangan-jangan, semua tanggapan dan reaksi kita tidak sungguh menyampaikan aspirasi demi kebaikan bersama, melainkan sebagai ajang show off yang melupakan norma-norma. Seyogyanya, kita semua bersikap reflektif terhadap kenyataan sosial, bukan reaktif. Presiden Jokowi pun menunjukkan agar sikap demokrasi kita hendaknya santun dan bermartabat, yakni menghargai semua orang. Dengan demikian, niscaya semua orang dapat merasakan manisnya buah keadilan dalam demokrasi. (Krisna Setiawan)[/vc_column_text][vc_single_image image=”5384″ img_size=”medium” add_caption=”yes” alignment=”right”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
“Demokrasi negara kita sudah kebablasan tanpa rem”
-Presiden Joko Widodo-
(dalam acara sebuah partai pada Rabu 22 Februari 2017 lalu)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]